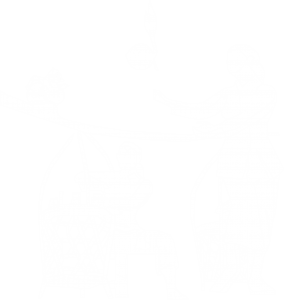Wanadadi, 17 Agustus 2025 – Mentari pagi baru menanjak di atas perbukitan Banjarnegara ketika lapangan Desa Wanakarsa mulai dipadati warga. Aroma tanah basah setelah embun, suara riuh anak-anak kecil berlarian, dan denting gamelan dari pengeras suara desa, menyatu menjadi latar perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.
Di sisi barat lapangan, tiga puluh siswa SMP Negeri 1 Wanadadi berbaris rapi. Mereka tampak sibuk memeriksa syal merah putih yang melingkar di leher, mengencangkan ikat pinggang, hingga memastikan bendera semaphore tergenggam kuat. Wajah-wajah remaja itu campuran antara gugup dan antusias—cerminan perjuangan kecil yang sudah mereka lalui selama berminggu-minggu.
“Deg-degan sekali, tapi kami sudah janji harus kompak,” bisik salah seorang penggalang, sambil melirik teman-temannya yang berusaha menyembunyikan senyum tegang.
Persiapan penampilan ini bukan perkara sehari. Sejak awal Juli, setiap sore selepas jam pelajaran, halaman sekolah berubah menjadi arena latihan. Kaki-kaki remaja itu menjejak tanah berdebu, tangan-tangan kecil mereka mengibaskan bendera dengan penuh tenaga. Tak jarang hujan sore membubarkan latihan, tapi mereka kembali lagi esoknya, mengganti seragam sekolah dengan pakaian olahraga, berlatih sampai senja menutup langit.
“Anak-anak luar biasa. Meski lelah, mereka tetap bersemangat. Yang membuat saya bangga, mereka sendiri yang minta latihan tambahan,” tutur salah satu guru pendamping, mengenang perjalanan panjang menjelang hari besar itu.
Dan tibalah saatnya. Usai bendera Merah Putih berkibar gagah di bawah langit biru Wanadadi, suara musik berirama cepat mengalun dari pengeras suara. Tiga puluh penggalang itu melangkah ke tengah lapangan. Ribuan pasang mata menoleh, menanti apa yang akan terjadi.
Seiring dentuman musik, gerakan mereka dimulai. Lengan-lengan terangkat, bendera semaphore dikibaskan dengan lincah. Setiap kibasan bukan sekadar estetika—melainkan simbol komunikasi pramuka yang pernah menjadi alat penting di masa perjuangan. Gerakan serentak itu seperti menyusun kata-kata tak terucap: tentang kedisiplinan, kesiapsiagaan, dan cinta tanah air.
Awalnya penonton hanya menyimak. Namun ketika gerakan semakin dinamis, suasana berubah. Anak-anak paskibraka yang baru saja menunaikan tugas ikut menggerakkan tangan. Tak lama, para guru, pejabat desa, forkompinca hingga warga yang duduk di kursi tamu undangan ikut bangkit. Lapangan Desa Wanakarsa sontak menjelma menjadi lautan manusia yang bergerak serempak, hanyut dalam satu irama kebangsaan.
Sorakan dan tepuk tangan membahana setiap kali rangkaian gerakan selesai. Beberapa orang tua tampak mengabadikan momen dengan ponsel, sementara yang lain terharu menyaksikan anak-anak mereka tampil dengan penuh percaya diri.
“Ini luar biasa. Rasanya kita semua seperti ikut menjadi bagian dari pertunjukan,” ujar Rahmat, seorang warga yang datang bersama keluarganya.
Bagi Kak Priyono, Ketua Kwaran Wanadadi, pertunjukan ini adalah lebih dari sekadar hiburan. “Kami ingin mengingatkan bahwa pramuka selalu relevan. Nilainya adalah persatuan, disiplin, dan pengabdian. Anak-anak inilah bukti bahwa semangat itu terus hidup,” katanya dengan suara bergetar.
Tepukan meriah menutup penampilan. Di bawah langit Agustus yang cerah, teriakan “Merdeka!” bergema panjang, menembus udara pagi Wanadadi. Bagi yang hadir, momen ini tak hanya meninggalkan kesan visual, tetapi juga perasaan haru: bahwa kemerdekaan adalah warisan yang harus dirawat, dihidupi, dan disebarkan melalui kreativitas tanpa batas.
Hari itu, di lapangan sederhana sebuah kecamatan, tiga puluh anak muda membuktikan bahwa nasionalisme tak selalu lahir dari pidato panjang atau seremoni besar. Ia bisa hidup dari gerakan sederhana—dari semangat kolektif yang membaurkan penampil dan penonton, hingga akhirnya menyatukan semua orang dalam satu tarian kebangsaan.***(abenn29_pusdatin.bna)
Narsum : pelatih_priyono
Editor : abenn29_pusdatin.kwarcab.bna